Syaikh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamd
Jika seseorang bertanya: Kita beriman kepada qadar, baik dan buruknya, yang berasal dari Allah, tetapi apakah dibenarkan menisbatkan keburukan kepada Allah Ta’ala? Apakah ada hal yang buruk dalam perbuatan-perbuatan-Nya?
Jawabannya: Allah Subhanahu wa Ta’ala adalah Mahasuci dari keburukan, dan tidak berbuat kecuali kebaikan. Qadar yang dinisbatkan kepada Allah tidak berisikan keburukan dalam satu segi pun. Sebab, ilmu Allah, pencatatan, masyii-ah dan penciptaan-Nya, semuanya itu murni kebaikan dan sempurna dari segala segi. Keburukan tidak boleh dinisbatkan kepada Allah dari satu segi pun, tidak dalam Dzat-Nya, tidak dalam Asma (nama-nama) dan Sifat-Nya, serta tidak pula dalam perbuatan-perbuatan-Nya.
Seandainya Dia melakukan keburukan, niscaya telah terambil suatu nama dari keburukan tersebut untuk-Nya, dan tidak akan pula semua Asma-Nya itu husna (indah), tetapi niscaya akan tertuju kepadanya hukum dari keburukan. Mahatinggi dan Mahasuci Allah (dari semua itu).
Keburukan hanyalah ada pada makhluk-Nya. Keburukan itu berada dalam apa yang ditentukan (al-maqdhi), bukan ada dalam ketentuan (al-qadha'). Ia menjadi buruk bila dihubungkan pada suatu tempat, dan baik bila dihubungkan pada tempat lainnya. Adakalanya menjadi baik bila dihubungkan pada tempatnya (atau tujuannya) dari satu sisi, sebagaimana ia buruk dari sisi lainnya, bahkan itulah yang umum.
Hal ini seperti qishash, penegakan hudud, dan membunuh orang-orang kafir. Hal itu buruk bagi mereka, bukan dari segala sisi, tetapi dari satu sisi saja, tapi baik bagi selain mereka karena berisi kemaslahatan untuk menjerakan, menghukum, dan menolak keburukan manusia satu sama lainnya. Demikian pula penyakit, meskipun buruk dari satu sisi, tetapi baik dari sisi-sisi lainnya.
Kesimpulannya, bahwa keburukan itu tidak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, karena terdapat keterangan dalam Shahiih Muslim bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menyanjung Rabb-nya dengan mensucikan-Nya dari keburukan, lewat do’a istiftah, yaitu dalam ucapan beliau:
...لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِيْ يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَاَلَيْتَ... .
“…Aku penuhi panggilan-Mu dengan senang hati, kebaikan seluruhnya ada di kedua tangan-Mu, dan keburukan tidaklah dinisbatkan kepada-Mu. Aku berlindung dan bersandar kepada-Mu, Mahasuci Engkau dan Mahatinggi… .”[1]
Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, mengomentari hadits ini, “Mahasuci dan Mahatinggi Allah dari penisbatan keburukan kepada-Nya, bahkan segala yang dinisbatkan kepada-Nya ialah kebaikan. Keburukan hanyalah menjadi keburukan karena terputus hubungannya kepada-Nya. Seandainya dihubungkan kepada-Nya, niscaya bukan suatu keburukan. Allah menciptakan kebaikan dan keburukan, lalu keburukan itu ada pada sebagian makhluk-Nya, bukan dalam penciptaan dan perbuatan-Nya.
Penciptaan, perbuatan, qadha', dan qadar-Nya adalah baik se-luruhnya. Karena itu Dia Subhanahu wa Ta’alasuci dari kezhaliman, yang mana ha-kikat dari kezhaliman itu sendiri ialah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Tidaklah Dia meletakkan sesuatu, kecuali pada tempatnya yang cocok, dan hal itu baik seluruhnya. Keburukan adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, jika diletakkan pada tempatnya, maka ia tidak buruk. Dengan demikian telah di-ketahui bahwa keburukan tidak dinisbatkan kepada-Nya, dan nama-nama-Nya yang husna membuktikan hal itu.”[2]
Ia juga mengatakan, “Nama-nama-Nya yang husna menghalangi penisbatan kejahatan, keburukan dan kezhaliman kepada-Nya, meskipun Dia Subhanahu wa Ta’alaPencipta segala sesuatu. Dia Pencipta manusia, perbuatan, gerakan, dan ucapan mereka. Jika hamba melakukan keburukan yang terlarang, maka hamba itu sendirilah yang telah melakukan keburukan.
Allah Subhanahu wa Ta’ala-lah yang membuatnya melakukan demikian. Penciptaan-Nya ini adalah keadilan, hikmah, dan kebenaran. Dia menjadikan orang yang berbuat (untuk kejelekan itu) adalah merupakan suatu kebaikan, sedangkan perbuatan yang dilakukan pelakunya adalah keburukan. Allah Subhanahu wa Ta’ala, dengan perbuatan ini, telah meletakkan sesuatu pada tempatnya, karena hal itu berisi hikmah yang mendalam yang Dia berhak dipuji karenanya, semua itu adalah kebaikan, hikmah, dan kemaslahatan, meskipun perbuatan yang terjadi dari hamba adalah dosa, aib, dan keburukan.”[3]
“Walhasil, bahwa keburukan tidaklah dinisbatkan kepada Allah Ta’ala, karena yang dimaksud dengan keburukan ialah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, yaitu kezhaliman, yang lawannya ialah keadilan, dan Allah adalah Mahasuci dari kezhaliman.
Jika yang dimaksudkan dengan keburukan adalah hukuman yang diberikan, disebabkan dosa yang dilakukannya, maka dengan Allah mengadakan sanksi atas dosa, hal itu bukanlah termasuk keburukan bagi-Nya, bahkan itu adalah keadilan dari-Nya.
Jika yang dimaksudkan dengan keburukan itu ialah tidak adanya kebaikan dan faktor-faktor yang menghantarkan kepada kebaikan itu, maka ketidakadaannya itu bukanlah perbuatan, sehingga bisa dinisbatkan kepada Allah. Hamba tidaklah memiliki hak terhadap Allah agar Dia memberikan taufik kepadanya, sebab hal ini adalah karunia Allah yang Dia berikan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan, menghalangi karunia bukanlah merupakan suatu kezhaliman dan bukan pula keburukan.”[4]
Syaikhul Islam rahimahullah berkata, “Allah Subhanahu wa Ta’ala tidak membutuhkan seluruh hamba-Nya. Dia hanya memerintahkan mereka kepada apa yang bermanfaat bagi mereka, dan melarang mereka dari apa yang membahayakan mereka. Dia berbuat baik kepada seluruh hamba-Nya dengan memerintahkan kepada mereka, dan berbuat baik kepada mereka dengan menolong mereka dalam ketaatan.
Seandainya, seorang alim yang shalih memerintahkan manusia kepada apa yang bermanfaat bagi mereka, kemudian dia membantu sebagian orang untuk melakukan apa yang ia perintahkan kepada mereka, dan tidak membantu yang lainnya, niscaya ia (dianggap) telah berbuat baik kepada mereka seluruhnya secara sempurna, dan tidak berbuat zhalim kepada orang yang ia tidak berbuat baik kepadanya.
Dan seandainya dia menghukum orang yang berbuat dosa dengan hukuman yang dituntut oleh keadilan dan kebijaksanaannya, nis-caya ia pun dipuji atas hal ini dan juga hal itu.
Bandingkanlah hal ini dengan kebijaksanaan Hakim Yang paling bijaksana dan Penyayang Yang paling menyayangi? Sebab, perintah-Nya adalah bimbingan, pengajaran, dan petunjuk kepada kebaikan. Jika Dia membantu mereka atas perbuatan yang diperintahkan, maka Dia telah menyempurnakan nikmat atas perkara yang diperintahkan, dan Dia disyukuri atas hal ini dan juga hal itu. Jika pun Dia tidak menolongnya, bahkan membiarkannya, sehingga ia me-lakukan dosa, maka dalam hal ini Dia mempunyai hikmah yang lain.”[5]
Kemudian jika seorang hamba telah mengetahui apa yang merugikan dan apa yang bermanfaat baginya, maka ia berkeharusan untuk tunduk kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga Dia menolongnya untuk melakukan apa yang bermanfaat baginya, dan tidak mengatakan, “Aku tidak akan berbuat, sehingga Allah menciptakan perbuatan padaku.” Demikian pula seandainya musuh atau binatang buas menyerangnya, maka ia harus lari dan tidak mengatakan, “Aku akan menunggu, hingga Allah menciptakan lari padaku.”[6]
Dari sini nampak jelas bagi kita bahwa keburukan itu tidak dapat dinisbatkan kepada Allah Azza wa Jalla.
[Disalin dari kitab Al-Iimaan bil Qadhaa wal Qadar, Edisi Indoensia Kupas Tuntas Masalah Takdir, Penulis Muhammad bin Ibrahim Al-Hamd, Penerjemah Ahmad Syaikhu, Sag. Penerbit Pustaka Ibntu Katsir]
_______
Footnote
[1]. HR. Muslim, kitab Shalaatul Musaafiriin, (I/535, no. 771).
[2]. Syifaa-ul Aliil, hal. 364-365. Lihat juga, Minhaajus Sunnah, (III/142-144), at-Tafsiirul Qayyim, hal. 550-556, Madaarijus Saalikiin, (I/409), Badaa-i’ul Fawaa-id, Ibnul Qayyim, (II/214-215), ar-Raudhah an-Nadiyyah, hal. 354-360, dan al-Hikmah fii Af’aalillaah, Dr. Muhammad bin Rabi’ al-Madkhali, hal. 199-204.
[3]. Syifaa-ul ‘Aliil, hal. 366 dan lihat juga hal, 366-385 dari buku yang sama. Lihat juga, Minhaajus Sunnah, (I/145-146 dan III/142-145), al-Hasanah was Sayyi-ah, Ibnu Taimiyyah, hal. 52-53, dan Thariiqul Hijratain, hal. 172-181.
[4]. Al-Hikmah wat Ta’liil fii Af’aalillaah, hal. 202, dan lihat pula, Daf’u Iihaamal Idhthiraab ‘an Aayaatil Kitaab, Syaikh ‘Allamah Muhammad al-Amin asy-Syanqithi, hal. 286-287.
[5]. Minhaajus Sunnah, (III/38). Lihat juga, al-Ikhtilaaf fil Lafzh, hal. 34-36, dan Risaalah ats-Tsaghar, hal. 85.
[6]. Lihat, al-Qadhaa' wal Qadar, al-Mahmud, hal. 280.
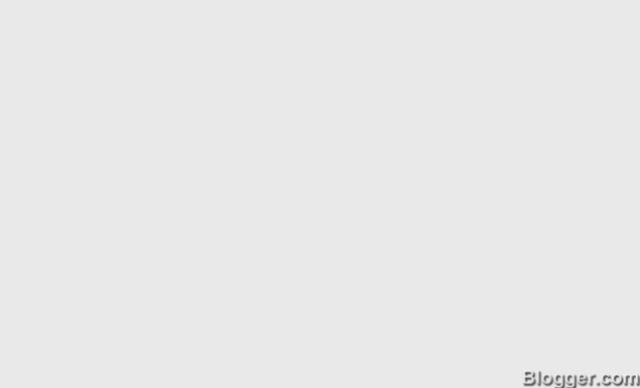
Posting Komentar Blogger Facebook